Chapter 05
CHASING REFLECTION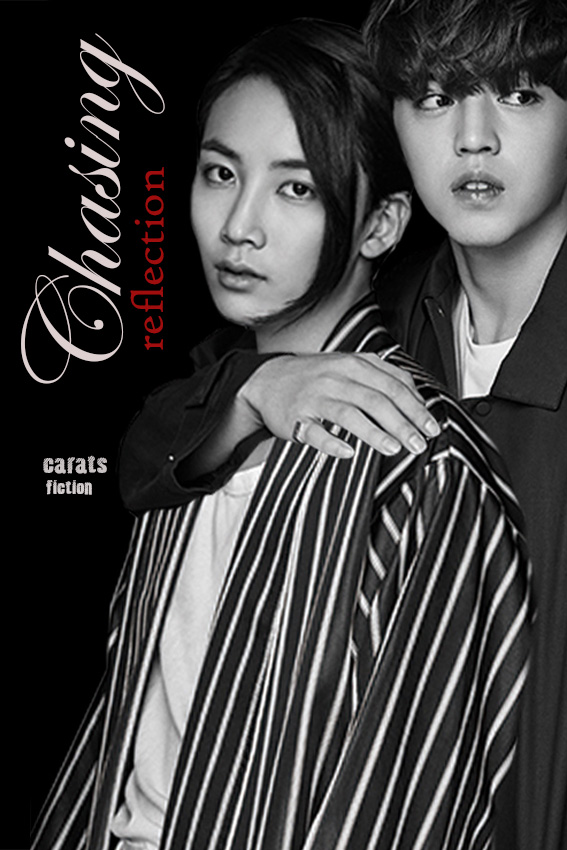
Rasanya perih ketika melihat orang yang selama ini kau pedulikan dan menjadi pusat seluruh perhatianmu, kini lebih dekat dengan orang lain. Setidaknya itulah yang Mingyu rasakan saat ia datang ke pameran untuk menyemangati sahabatnya. Alih-alih bertemu dengan Jeonghan, ia malah melihat laki-laki yang menjadi model lukisan Jeonghan itu—bersama temannya—sedang berdiri di depan lukisan Jeonghan.
Ia tidak melihat sosok Jeonghan di manapun.
Dari kejauhan ia mengamati laki-laki yang namanya Seungcheol itu berlari ke kamar mandi dan tak lama kemudian ia keluar bersama Jeonghan. Yang membuat Mingyu pedih adalah sikap Seungcheol yang sok akrab—lelaki itu merengkuh bahu Jeonghan dan mereka tertawa-tawa bersama.
Apa-apaan itu? Mingyu memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin lagi melihat Jeonghan bersama lelaki itu. Menyebalkan sekali. Perasaan ‘terbuang’ menyeruak di hati Mingyu. Semula ia ingin datang untuk menyemangati Jeonghan namun melihat sahabatnya itu sudah terhibur dengan keberadaan Seungcheol, lebih baik Mingyu pergi saja.
Ia tidak mau tahu lagi tentang cermin itu. Peduli setan.
Langkahnya tergesa-gesa menuju ruang penyimpanan. Ia berdiri di hadapan cermin itu. Matanya menelisik mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk memecahkannya. Ia menemukan tongkat bisbol di dekat situ. Diraihnya tongkat tersebut dan ia bersiap untuk mengayunkannya ke arah cermin. Namun begitu sudah tinggal beberapa senti tongkat bisbol menyentuh cermin, Mingyu menghentikan niatnya.
Tongkat bisbol terjatuh ke lantai menimbulkan bunyi keras, diikuti tubuh Mingyu yang jatuh terduduk. Nafasnya tak beraturan. Ia heran dengan perasaan marahnya ini—tak pernah ia merasa emosi separah ini.
Mingyu lantas mengeluarkan ponsel dari saku celana. Ia menghubungi seseorang, “Wonwoo-ssi, kau ada di toko?”
“Tidak, Mingyu-ssi. Aku ada di rumah pelanggan yang ingin menjual barang antiknya. Ada apa?”
“Bolehkah kususul ke sana? Aku harus mencari udara segar.”
“Uh, kau di kampus ya? Lokasiku cukup jauh dari kampusmu. Tidak apa-apa kah?”
Mingyu tersenyum kecut. Asalkan tidak di dekat Jeonghan, ia tidak masalah, “Tidak apa-apa, Wonwoo-ssi. Tolong kirimkan alamatnya.”
“Baiklah, tunggu sebentar.”
***
Wonwoo memandang ponselnya dengan bingung. Tidak biasanya Mingyu terdengar begitu putus asa sampai-sampai ingin menyusulnya di tempat yang cukup jauh. Ia mengedikkan bahu setelah mengirimkan alamat tempatnya berada pada Mingyu. Ia lantas kembali ke dalam ruangan, tempat ia berbincang-bincang pada pelanggan setia toko milik almarhum pamannya itu.
“Maaf menyita waktu Anda. Mari kita lanjutkan lagi, Paman.” Wonwoo meminta maaf pada pelanggannya tersebut.
“Bagaimana menurutmu? Kira-kira akan kau bayar berapa jam antik ini? Kau bisa menaksir perkiraan harganya kan, Wonwoo-ssi?”
Wonwoo menjawabnya dengan anggukan lantas menunjukkan kalkulator yang telah tertulis perkiraan harganya. Lelaki itu mengangguk puas. Seakan teringat sesuatu yang penting, lelaki itu menjentikkan jarinya.
“Oh ya, aku ingin menunjukkan ruangan baruku. Tempat menyimpan semua koleksi barang antikku. Kau pasti menyukainya, Wonwoo-ssi. Aku terinspirasi dengan toko pamanmu itu.” Ia mengajak Wonwoo ke ruangan barunya yang terletak di bagian belakang rumahnya yang besar.
Wonwoo menurut saja. Ia berjalan di belakang lelaki yang sudah lama menjadi pelanggan di toko pamannya itu. Begitu pintu ruangan dibuka, perhatian Wonwoo langsung tertuju pada satu benda yang diletakkan tepat di seberang pintu masuk—cermin antik itu. Jantungnya berdebar-debar, meski bukan ia yang kehilangan pantulan. Ia teringat cerita Mingyu.
“Paman, itu cermin antik yang dibeli dari toko kami, ya?” Telunjuknya terarah pada cermin itu.
“Ya benar sekali! Cermin itu indah kan jika diletakkan di tempat yang tepat. Kau perhatikan saja ukirannya, sungguh langka. Kira-kira siapa yang membuatnya, ya? Kau tahu, Wonwoo-ssi?”
Wonwoo menggelengkan kepalanya, “Saya tidak tahu.” Ia membatin, bila ia tahu pasti sudah menceritakannya pada Mingyu, “Oh ya Paman, apa terjadi hal-hal aneh sejak Anda membeli cermin ini?”
“Tidak. Memangnya kenapa?”
Wonwoo memutar otak untuk mencari alasan yang tepat. Tidak mungkin ia menceritakan mengenai kejadian aneh yang menimpa Jeonghan, “Almarhum paman saya lupa mendoakan cermin ini di pendeta. Biasanya kami mendoakan barang-barang antik sebelum kami jual. Hanya untuk berjaga-jaga saja.” Wonwoo membual.
“Oh begitu. Kalau menurutmu perlu didoakan ke pendeta, ya sudah katakan kapan kau akan membawa pendeta kemari. Biar kusiapkan ruangannya.”
“Ya, Paman. Saya akan menghubungi Paman bila pendetanya sudah siap.” Ia kembali memusatkan perhatian pada cermin di depannya itu. Ia meminta izin untuk menyentuh cermin tersebut.
Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Pantulan di cermin itu tetaplah seorang Jeon Wonwoo. Ia juga tidak merasakan aura negatif yang menguar dari cermin tersebut.
“Kau sepertinya tertarik dengan cermin itu, ya?”
“Bukannya begitu. Saya tidak pernah memerhatikan cermin ini ketika masih ada di gudang toko kami. Ternyata ukirannya memang indah. Terlihat sangat elegan.”
“Seleramu memang bagus, Wonwoo-ssi. Oh ya, kalau begitu kau datang ke pesta perkumpulan kolektor barang antik di rumahku. Besok malam. Kau boleh ajak bibimu atau temanmu. Bagaimana?”
“Pesta kolektor? Uhm...” Wonwoo ragu-ragu. Ia tidak pernah datang ke pesta. Jas yang ia miliki hanya satu, yang ia gunakan ke pemakaman pamannya. Dan ia juga tidak mungkin mengajak bibinya. Semenjak pamannya meninggal dunia, bibi berubah sikap menjadi sedikit aneh.
“Sudahlah, tidak perlu kau pikir-pikir. Kau harus datang! Ini juga bisa sebagai ajang promosi toko pamanmu, kan.” Lelaki itu menepuk keras bahu Wonwoo.
“Ya Paman, aku akan datang.”
***
“Pesta perkumpulan kolektor barang antik? Kau serius?” Mingyu memandang Wonwoo tidak percaya. Jelas saja tidak percaya sebab Wonwoo mengajaknya datang ke pesta perkumpulan kolektor barang antik—yang terdengar sangat eksklusif. Sedangkan Mingyu saja tidak tahu menahu soal barang antik. Ia pun tidak suka berada di museum.
Wonwoo menunduk, memandang sisa kue cokelat yang ada di tangannya, “A-aku tidak pernah pergi ke pesta, Mingyu-ssi. Aku tidak percaya diri pergi sendirian. Kau tidak keberatan menemaniku, kan?”
Mingyu menyandarkan tubuhnya di bangku taman. Cukup lama ia berpikir. Ia tidak suka pesta yang penuh basa-basi tapi kalau sekedar menemani Wonwoo saja mungkin tidak masalah, “Mereka menyediakan makan malam, kan?” gurau Mingyu. Wonwoo tersenyum menggeleng tak percaya.
“Kau memikirkan makanan? Ya tentu saja mereka menyediakan buffet. Tapi kita harus mengenakan setelan jas.” Membayangkannya saja sudah membuat Wonwoo keringat dingin. Ia tak tahan mengenakan pakaian resmi dalam waktu lebih dari satu jam. Rasanya sesak.
“Tidak masalah. Aku sangat tampan mengenakan jas—” Menyadari ia tidak sedang bicara dengan Jeonghan, Mingyu buru-buru menghentikan ucapannya. Ia terbiasa mengatakan hal narsis di depan Jeonghan namun sekarang ia sedang bersama Wonwoo yang baru dikenalnya beberapa hari. Memalukan sekali bila bersikap narsis.
Terbukti, Wonwoo menahan tawa mendengar kepercayaan diri Mingyu yang luar biasa itu, “Ya, aku percaya kau terlihat tampan mengenakan jas.”
“Wonwoo-ssi, tolong jangan bahas itu lagi. Aku kan hanya bergurau.” Mingyu menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Ia sangat malu. Tawa Wonwoo meledak. Rasanya Mingyu ingin menenggelamkan diri ke laut saja.
Setelah Wonwoo puas menertawakan Mingyu, lelaki itu tampaknya ingin mengatakan sesuatu sejak tadi namun ditahan.
“Tentang cermin itu...”
Jantung Mingyu berdetak lebih cepat. Ia tidak ingin mendengar apapun tentang cermin itu. Bisa-bisa emosi yang sejak tadi ditahan, akan meledak seketika.
“Wonwoo-ssi, aku sedang tidak ingin mendengar tentang cermin itu. Aku sudah bosan. Bagaimana kalau kau ceritakan tentang dirimu saja?”
Semburat merah muda nampak di wajah Wonwoo. Walau mungkin ini sekedar basa-basi, Wonwoo bersemangat saat seseorang ingin mengetahui tentang dirinya. Ia bukan orang yang suka menyembunyikan sesuatu mengenai dirinya, sebab tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan.
“Kalau begitu, kita main tebak-tebakan saja. Kita bergantian menanyakan satu pertanyaan tentang diri masing-masing. Biar adil.” usulan Wonwoo segera diiyakan oleh Mingyu, “Kau duluan.”
Tak terasa waktu berlalu dengan cepat ketika mereka bermain tebak-tebakan. Perasaan kesal Mingyu seakan perlahan-lahan menguap. Kebersamaannya dengan Wonwoo sudah menghibur Mingyu. Ia bisa tertawa, tidak seperti tadi siang saat ia lebih banyak murung. Menghabiskan waktu bersama Wonwoo ternyata menyenangkan. Anehnya ia bisa membicarakan bermacam-macam hal, padahal ia baru mengenal lelaki yang duduk di sampingnya itu.
Dari cerita Wonwoo, Mingyu baru mengetahui bahwa lelaki itu yatim piatu dan selama ini yang mengurusnya adalah almarhum paman dan bibi yang aneh itu, sehingga wajar saja bila Wonwoo begitu mengabdi pada paman-bibinya. Mingyu juga baru tahu bahwa terpaut setahun lebih tua darinya, namun lelaki itu tidak melanjutkan ke jenjang kuliah.
“Kenapa?” tanya Mingyu penasaran. Ia tahu tidak sopan bertanya seperti itu tapi apa boleh buat, ia penasaran.
“Aku belum beruntung untuk mendapatkan beasiswa. Jadi aku lebih memilih mengikuti kursus-kursus singkat saja, seperti kursus komputer. Nantinya aku juga mengikuti pelatihan menjadi guru komputer. Siapa tahu aku bisa mengajar di kursus juga.”
Pikiran Mingyu dipenuhi segala sesuatu tentang dirinya. Ia semestinya bersyukur bisa melanjutkan jenjang kuliah tanpa perlu memikirkan biaya dan mencari beasiswa. Ia jauh lebih beruntung daripada Wonwoo. Setidaknya ia bisa menyalurkan sedikit ilmunya pada Wonwoo sebagai rasa syukurnya.
“Kau mau belajar musik padaku?” tawar Mingyu.
Wajah Wonwoo berubah cerah, “Kau mau mengajariku? Uhm, apakah biayanya mahal?” Tiba-tiba Wonwoo jadi ragu bila berkaitan dengan biaya.
Mingyu tersenyum lebar, “Kau hanya perlu membelikanku kue saja. Bagaimana?”
“Tentu saja aku mau. Tapi... kau juga mau menemaniku ke pesta besok, kan?”
“Hmm... bagaimana ya?” Mingyu berlagak berpikir.
“Mingyu-ssi,” Wonwoo mengatupkan kedua tangannya, tanda memohon. Mingyu tidak bisa menolaknya.
***
Tatapan Jeonghan nanar memandang ke arah rumahnya. Ia ragu melangkahkan kaki ke dalam. Rasanya amarahnya masih belum bisa dikendalikan bila mengingat ucapan ayahnya yang menyakitkan saat pameran itu. Ia tidak ingin pulang tapi ia juga tidak tahu harus ke mana.
Orang pertama yang terpikir di otaknya adalah Mingyu namun mengingat Mingyu tidak muncul sama sekali ke pamerannya, membuat Jeonghan kecewa, sehingga ia mengurungkan niat untuk menghubungi Mingyu. Ia berpikir Mingyu akan datang pertama kali dan memberikan ucapan selamat—seperti yang dilakukan Seungcheol padanya. Tapi itu hanya angan Jeonghan, buktinya hingga selesai pameran, sosok sahabatnya itu tidak muncul. Begitu pula dengan telepon dan pesan yang dikirim Jeonghan, tidak ada satupun yang dijawab oleh Mingyu.
Jeonghan mengamati nomor-nomor kontak yang ada di ponselnya. Ia tersenyum miris karena sebagaian besar nomor kontak yang ia simpan adalah teman-teman yang tidak begitu ia kenal akrab. Kalau dipikir, ia bahkan tidak memiliki teman akrab selain Mingyu.
Ia berjongkok di dekat pagar rumahnya untuk menenangkan pikiran sembari menimbang-nimbang untuk pulang ke rumah atau tidak. Ponselnya bergetar, seseorang menghubunginya. Foto selfie-nya bersama Seungcheol berpendar di layar ponselnya dan nama kontaknya tertulis ‘Choi Seungcheol’.
Sembari mengulum senyum, Jeonghan menyahut, “Ada apa lagi, Seungcheol-ssi?”
“Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengabarkan, aku sudah sampai rumah dengan selamat. Bagaimana denganmu, hyung?”
“Aku malas masuk ke dalam rumah. Teringat semua kata-kata ayahku, rasanya aku ingin memukul sesuatu.”
“Kau tidak boleh berkata begitu, hyung. Itu ayahmu. Dan kau tetap harus masuk ke rumah, mandi lalu tidur.”
“Kau perhatian sekali, Seungcheol-ssi. Tapi aku sudah dewasa. Aku tidak suka perlakuan ayahku yang sama sekali tidak menghargaiku sebagai manusia.” Ia mendengus.
Tidak ada sahutan dari Seungcheol. Jeonghan tahu bahwa Seungcheol setuju dengan perkataannya hanya saja lelaki itu tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkan Jeonghan.
“Hyung, kau ingin kutemani jalan-jalan? Ke mana?” tanya Seungcheol tiba-tiba. Jeonghan menaikkan satu alisnya, ia sendiri tidak tahu mau ke mana. Yang penting ia tidak ingin pulang ke rumah.
“Aku ada ide.”
***
“JEONGHAN-HYUUUUUUUUNGGGGG!!! AAAAAARRRRGGHHH!!!”
Teriakan Jeonghan pun terkalahkan dengan teriakan Seungcheol. Itu namanya bukan teriakan melainkan pekikan histeris seperti seorang gadis yang ketakutan. Sebenarnya Jeonghan ingin terbahak-bahak, tapi laju roller coaster membuatnya kembali berteriak, begitu juga Seungcheol. Tak lupa lelaki itu menambahi dengan umpatan-umpatannya tiap kali roller coaster itu menukik atau menanjak.
“TUNGGU PEMBALASANKU, JEONGHAAAAAAAAAAN!!!”
Jeonghan melirik lelaki yang duduk di sampingnya itu. Seungcheol mencengkeram erat besi pegangan di depannya, matanya juga terpejam, dengan dahi mengerut. Lucu sekali Seungcheol ini. Jeonghan berteriak seraya tertawa—ia jadi terdengar seperti orang jahat saja.
Seusai mereka turun dari roller coaster, Seungcheol meminta waktu lima menit untuk menenangkan diri di kursi terdekat. Ia mengipasi wajah dengan tangannya dan Jeonghan merasa bersalah. Ini semua adalah idenya. Ia suka sekali menghabiskan waktu bermain roller coaster bila sedang stres dan butuh berteriak. Siapa sangka Seungcheol fobia ketinggian. Jeonghan mengangsurkan botol minumannya pada Seungcheol. Lelaki itu menerimanya lalu meneguk habis semua isinya, sama sekali tak menyisakan setetespun untuk Jeonghan.
“Aku minta maaf, Seungcheol-ssi. Aku tidak tahu kau setakut itu.”
Seungcheol cemberut, “Aku tidak ingin terlihat penakut. Memalukan sekali menjadi lelaki penakut.”
Jeonghan duduk di samping Seungcheol, menunggunya hingga lebih tenang sebelum mengajaknya masuk ke rumah hantu. Entah mengapa ia ingin mengerjai Seungcheol hari ini. Sifat jahilnya memaksa muncul bila bertemu Seungcheol.
“Sudah lebih tenang? Siap dengan permainan selanjutnya?”
Kedua mata Seungcheol memicing, “Aku tidak mau tertipu lagi. Kita jalan-jalan saja, hyung.” Ia berdiri. Seolah sudah terbiasa, ia menggenggam tangan Jeonghan tanpa rasa canggung. Justru Jeonghan yang merasa panik—sungguh panik, tangannya digenggam oleh Choi Seungcheol. Jantungnya berdebar kencang.
“Seungcheol-ssi, kita harus mencoba beberapa permainan lagi. Tidak seru kalau cuma satu permainan saja.” Meski berdebar-debar, Jeonghan masih bisa mengendalikan diri dan memaksa Seungcheol untuk menaiki wahana lainnya.
“Ya tapi tidak perlu yang tinggi seperti itu, hyung.”
Jeonghan mengutarakan salah satu dari seribu alasannya, “Tapi kalau dari ketinggian, langit malam dan bintang-bintangnya terlihat indah.”
Seungcheol menghentikan langkahnya. Ia membalikkan tubuh menatap Jeonghan, “Hyung ingin melihat langit malam? Kita bisa ke atap sekolahku. Dari situ bintangnya juga terlihat indah.”
“Bu-bukan begitu maksudku! Ya sudah, kita ke rumah hantu saja.” Giliran Jeonghan yang menarik tangan Seungcheol menuju arah berlawanan yakni arah ke rumah hantu. Seungcheol tidak mau bergerak.
“Yoon Jeonghan-hyung, kau mau menyiksaku?”
“Hmmph,” Jeonghan menahan tawa. Senang sekali ia menyaksikan tatapan ketakutan di mata Seungcheol.
Lelaki itu menghela nafas panjang, menyerah, “Huff, baiklah hyung. Hari ini saja kau boleh mengerjaiku sepuasnya. Asalkan kau tidak sedih lagi, aku tidak masalah. Ayo sekarang cepat beli tiketnya.”
Jeonghan terpaku di tempatnya.
Asalkan kau tidak sedih lagi, aku tidak masalah.
Mengapa Seungcheol mengatakan hal itu? Jeonghan menggelengkan kepala—berusaha menghilangkan rasa penasarannya pada ucapan Seungcheol. Lelaki itu membalikkan tubuh begitu menyadari Jeonghan tidak mengikutinya. Ia kembali menghampiri Jeonghan lalu menggenggam tangan Jeonghan—lagi.
Mata Jeonghan membelalak terkejut.
“Ayo, Jeonghan-hyung. Apa kau berubah pikiran tidak mau mengerjaiku lagi?”
***
Seluruh energi Seungcheol sudah terkuras setelah hampir dua jam lebih ia berteriak, memekik, kadang tertawa—entahlah sudah berapa macam emosi yang ia tunjukkan. Yang jelas tiap kali ia ketakutan, Jeonghan terbahak-bahak, hingga pada satu titik Seungcheol berpura-pura ketakutan hanya agar Jeonghan bisa menertawakannya.
Ia sudah gila.
Namun pembelaan diri Seungcheol adalah karena ia ingin membuat Jeonghan tersenyum senang setelah ucapan ayahnya tadi siang itu meruntuhkan harapan Jeonghan.
“Kau sudah puas menertawakanku, hyung?” Seungcheol berpura-pura cemberut. Jeonghan yang berjalan di sampingnya masih memegangi perut kemudian mengusap airmata karena terlalu banyak tertawa.
“Maaf, tapi wajahmu lucu sekali kalau ketakutan.”
Seungcheol berakting kesal. Ia menunjuk wajahnya sendiri, “Hyung, ini pertama dan terakhir kali aku menunjukkan wajah ketakutan. Jadi kau harus ingat baik-baik. Aku tidak mau mengulanginya lagi.”
“Aku mengerti.” Jeonghan mengeluarkan ponselnya lantas mengambil foto Seungcheol tanpa memberinya peringatan lebih dulu hingga Seungcheol berkedip kaget, “Makanya harus kuabadikan di foto.”
“Jeonghan-hyung!” Seungcheol berusaha merebut ponsel Jeonghan dan lelaki itu mengangkat tangannya yang memegang ponsel lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Dalam aksi perebutan ponsel itu, tanpa sadar kedua tangan Seungcheol merengkuh tubuh Jeonghan seakan menariknya dalam pelukan.
Jeonghan membeku. Seungcheol segera menghentikan aksinya seusai menyadari perubahan air muka Jeonghan. Ia merasa sudah kelewat batas terhadap seseorang yang baru dikenalnya beberapa hari. Semestinya ia tidak bisa menyamakan perlakuannya pada Jeonghan dan pada Seungkwan. Seungcheol sudah terbiasa menghina atau memeluk Seungkwan sembarangan.
Tapi ini adalah Yoon Jeonghan. Lelaki imut yang membuatnya berpikir yang tidak-tidak.
Bila ia bersikap melebihi batas, ia tidak yakin apa bisa berpikir lurus lagi.
“Ma-maafkan aku, hyung.” Ia membungkukkan tubuh di hadapan Jeonghan, “Aku tidak sengaja.”
“Tidak apa-apa, Seungcheol-ssi. Ayo kita pulang saja.”
Senyum Seungcheol merekah mendengar Jeonghan sudah mau kembali ke rumahnya. Itu tandanya lelaki itu sudah tidak marah lagi pada ayahnya atau setidaknya sudah mengurangi kemarahannya.
“Ayo, kuantar kau pulang ke rumah.”
“Uh,” Jeonghan menarik lengan Seungcheol untuk menghentikan langkahnya, “Aku tidak ingin pulang ke rumahku.”
“Hah? Lalu pulang ke mana?” Ia benar-benar dibuat bingung oleh kelakuan lelaki imut itu.
Jeonghan tersenyum canggung. Ia menggaruk kepalanya, “Bolehkah aku menginap semalam di rumahmu, Seungcheol-ssi?”
Seungcheol merasa pendengarannya menurun atau mungkin berhalusinasi karena terlalu banyak berteriak.
“Apa?”
“Kalau kau mengizinkan, boleh aku menginap di rumahmu dulu?”
Bagaimana mungkin Seungcheol tega menolak permintaan Jeonghan apalagi disertai senyum yang seperti itu? Tentu tidak tega.
“Hubungi ayahmu dulu, hyung.”
***
Kesan pertama ketika Jeonghan menginjakkan kakinya di rumah Seungcheol adalah indah dan elegan. Ia menyukai desain interior dengan banyak cermin dan kaca jendela. Satu hal yang paling Jeonghan sukai adalah ke manapun ia berpaling, ia akan melihat pantulan Choi Seungcheol. Sejak kapan ia kecanduan melihat wajah Seungcheol?
Tapi tampaknya Seungcheol tidak merasakan hal yang sama. Buktinya ketika ia memasuki rumah, ia langsung berjalan sambil menunduk dan terkadang menggunakan kedua tangannya untuk menutupi samping mata agar tidak terpapar langsung dengan cermin. Begitu juga sewaktu memasuki kamar Seungcheol, cermin di kamarnya tertutup selimut. Jeonghan kecewa dengan sikap lelaki itu. Kesedihan yang sempat menguap, kembali lagi.
Sepertinya Seungcheol menyadari aura Jeonghan yang berbeda. Ia yang semula bersemangat untuk menginap, kini menampakkan wajah murungnya lagi. Jeonghan menggeser tubuhnya ketika Seungcheol duduk di sampingnya. Seungcheol mendekat lagi, Jeonghan menggeser tubuhnya dan seterusnya hingga berulang lagi. Namun saat tubuh Jeonghan terpojok di dinding, ia tak bisa ke mana-mana dan memilih untuk berpura-pura memainkan ponselnya.
“Hyung, tidurlah di ranjangku. Biar aku di bawah saja.”
“Kenapa?” Jeonghan mengerutkan dahi. Sejak kapan tamu mendapat keistimewaan tidur di ranjang sedangkan pemilik rumah malah tidur di lantai?
Seungcheol tidak menyahut, alih-alih menarik selimut yang semula digunakan untuk menutupi cermin. Ia menggelar selimut itu di lantai dan mengambil satu bantal dari ranjangnya. Jeonghan semakin terkejut karena Seungcheol tidur hanya beralaskan selimut, bukan kasur lipat.
“Aku sudah biasa tidur di lantai bila Seungkwan menginap. Ia tidak bisa tidur di lantai, katanya bisa merusak metabolisme dan mengurangi keindahan kulit wajahnya. Dasar Seungkwan.” Ia menggeleng-gelengkan kepala tak percaya, lalu melanjutkan, “Dan kau memiliki kulit yang indah jadi aku tidak akan membiarkanmu tidur di lantai.”
Mendapat pujian kulit indah, Jeonghan menunduk malu. Hilang sudah rasa kesalnya pada Seungcheol. Ia benar-benar tak bisa mengendalikan emosinya di hadapan pemuda itu, entah kenapa. Seungcheol pun mengangsurkan kaos, celana piyama dan handuk kepada Jeonghan lalu menyuruhnya mandi dulu sebelum tidur. Tidak hanya itu, seusai Jeonghan mandi, ia mendapati segelas susu cokelat hangat di meja belajar Seungcheol.
“Untukmu, hyung. Supaya tidurmu nyenyak.” Seungcheol tersenyum sembari menepuk bahu Jeonghan.
Bahkan setelah lampu dimatikan dan tubuh tertutup selimut, debaran jantung Jeonghan masih kencang. Ia tidak bisa tidur.
“Seungcheol-ssi,” panggilnya lirih.
Tidak ada sahutan dari arah bawah ranjang. Jeonghan memiringkan tubuhnya agar bisa lebih leluasa memerhatikan Seungcheol. Lelaki itu sudah memejamkan mata dan dengkuran halus terdengar dari bibirnya. Telunjuk Jeonghan terulur untuk menyentuh ujung hidung Seungcheol. Dengan hati-hati ia mengarahkan telunjuknya ke bibir pemuda itu. Setiap detail wajah Seungcheol ia amati. Walaupun ia bisa melihat pantulan lelaki itu di cermin, mengamati secara langsung terasa berbeda. Jeonghan tiba-tiba ingin melukis.
Ketika pikirannya melayang, Jeonghan mendengar deheman dari arah Seungcheol. Ia buru-buru menarik telunjuknya. Jeonghan berpura-pura memejamkan mata, tidur.
“Aku tahu kau belum tidur, Yoon Jeonghan-hyung.” Seungcheol terduduk, rambut acak-acakan dan mata setengah tertutup, “Apa perlu kuambilkan sesuatu? Apa AC nya terlalu dingin, hyung?”
Kini Jeonghan mulai paham mengapa ia sering tidak bisa mengendalikan debaran jantungnya di dekat lelaki ini. Perhatian Seungcheol akan hal-hal terkecil sekalipun yang membuat Jeonghan kagum.
“Tidak ada apa-apa, Seungcheol-ssi. Aku hanya... tidak bisa tidur.”
Sosok Seungcheol tiba-tiba berpindah ke ranjang yang sama dengan Jeonghan. Ia menyibak selimut lalu dengan tenangnya menggeser tubuh Jeonghan agar memberinya ruang untuk berbaring. Lelaki itu memiringkan tubuhnya menghadap Jeonghan yang terlentang tak bergerak.
Jeonghan mengumpat dalam hati, otaknya tak bisa memproses semua ini. Choi Seungcheol yang hanya berjarak beberapa senti darinya—tidak, tubuh mereka sudah bersentuhan, bahkan hangat hembusan nafas Seungcheol terasa di lehernya.
“Kutemani biar tidak mimpi buruk.” bisik Seungcheol di telinganya.
Jeonghan menggigit bibir sambil memohon dalam hati agar Seungcheol tidak mendengar debarannya. Bagaimana ia bisa tidur kalau begini caranya? Dipaksa memejamkan mata pun sulit karena disampingnya ada Seungcheol.
“Kau tidak nyaman, hyung?” Lelaki itu sedikit memundurkan tubuhnya dari Jeonghan, menyadari ia tidak bergerak dan menahan nafas.
“Bu-bukan karena itu.” potongnya cepat. Ia tidak ingin Seungcheol salah sangka.
Meski dalam gelap, samar-samar ia bisa menangkap senyuman hangat Seungcheol. Lelaki itu merapikan selimut yang menutupi tubuh mereka dan kembali berbaring. Kini Jeonghan memberanikan diri untuk menatap Seungcheol.
“Kenapa kau baik padaku, Seungcheol-ssi?”
Seungcheol terkekeh, “Ya, hyung! Aku kan memang baik ke semua orang.” Jeonghan mengerucutkan bibirnya, tidak suka gurauan Seungcheol. Lelaki itu berdehem lalu meralat jawabannya, “Karena Jeonghan-hyung adalah pantulanku dan itu artinya menjadi bagian dari diriku. Aku tidak mau melihat pantulanku bersedih. Kurasa hyung akan melakukan hal yang sama padaku, iya kan hyung?”
Mungkin lebih dari itu, batin Jeonghan. Tapi tak sampai hati untuk mengucapnya.
“Hyung,”
“Ya?”
“Aku beruntung bisa cepat menemukanmu karena yang kudengar dari pemilik toko barang antik itu, bila kita tidak segera bertemu maka akan terjadi sesuatu yang buruk...”
Alis Jeonghan bertaut, “Buruk seperti apa?”
“Entahlah. Orang itu tidak mau menceritakan padaku. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengembalikan pantulan kita seperti dulu.”
Jeonghan menghela nafas panjang. Ia tidak pernah berpikir seperti itu.
“Ini sudah malam. Ayo kita tidur, hyung.”
Dan malam itu pikiran Jeonghan terbagi dan membuat matanya sulit terpejam.
***
Jisoo bukan tipikal murid pintar yang suka duduk di kursi paling depan. Baginya memahami pelajaran tidak ada kaitannya dengan posisi duduk, kecuali bagi sebagaian besar murid yang ingin mencontek tentu saja kata-kata ‘posisi menentukan prestasi’ itu dibenarkan.
Ia lebih memilih duduk di kursi paling belakang, di pojok kelas, dekat dengan jendela. Siswi-siswi di kelasnya sering menganggapnya meniru adegan drama di mana pemeran utamanya yang tampan duduk di pojok kelas dan memandang ke arah jendela dengan melankolis. Dari segi wajah dan prestasi, Jisoo memang cocok sekali dijadikan pemeran utama di drama. Tapi ia lebih tertarik untuk meretas daripada menjadi aktor.
Yang membuat Jisoo terlihat lebih keren dari siswa-siswa lainnya adalah keahliannya berbahasa Inggris. Menghabiskan masa kecilnya di Sydney memang memperlancar bahasa Inggrisnya. Logatnya yang seperti native speaker itu terdengar begitu seksi di telinga siswi-siswi. Dan kelebihannya itu terkadang menyusahkan Jisoo.
Seperti sekarang ini.
Dikarenakan berita mengenai kelebihan Jisoo itu sudah menyebar bagai virus, kini ia berada di rumah Kepala Sekolah Seo untuk membantu beliau sebagai penerjemah pribadi di pesta yang diadakan beliau. Rencananya Kepala Sekolah Seo akan mengundang beberapa kolega dari luar negeri yang tentunya akan menggunakan bahasa Inggris.
Jisoo sebenarnya tidak pernah menyukai acara pesta resmi, terlebih lagi ia diwajibkan mengenakan setelan jas. Canggung sekali berkeliaran sendirian di pesta, menunggu Kepala Sekolah Seo memberi kode ketika teman-temannya dari luar negeri itu datang. Ia tak bisa pergi terlalu jauh dari Kepala Sekolah Seo.
“Hong Jisoo,” Kepala Sekolah Seo melambaikan tangan ke arahnya. Jisoo berjalan menghampirinya yang sudah didampingi dua lelaki asing paruh baya. Jisoo membungkukkan tubuh ketika harus memperkenalkan diri sebagai penerjemah Kepala Sekolah Seo.
Kedua teman Kepala Sekolah Seo, Mr. Wyatt dan Mr. Harper dari Amerika, memuji dan berterimakasih karena telah mengundang mereka ke pesta itu. Kemudian Kepala Sekolah Seo mengajak teman-temannya untuk melihat ruangan khusus tempatnya memamerkan koleksi barang antiknya.
Jisoo terdiam sejenak. Dalam pikirannya hanya ada satu hal : cermin Seungcheol—yah walaupun itu bukan milik Seungcheol.
Rupanya tidak hanya mengajak Mr. Wyatt dan Mr. Harper, melainkan semua orang yang datang ke pesta tersebut. Kepala Sekolah Seo mengadakan pesta ini sekaligus untuk meresmikan ruang pribadinya yang menyimpan barang-barang antik. Rencana ke depannya, ruang tersebut akan dibuka untuk umum sebagai pameran—itu bila koleksinya sudah semakin banyak, begitu kata beliau. Jisoo menyimak sembari terus menerjemahkan ucapan Kepala Sekolah Seo pada Mr. Wyatt dan Mr. Harper.
Kepala Sekolah Seo mempersilakan mereka masuk dan menikmati barang koleksinya. Ruangan itu memang cukup besar untuk menampung banyaknya barang antik milik Kepala Sekolah Seo. Jisoo sudah ingin sekali mendekati cermin itu, namun kedua orang asing yang ia ikuti itu masih sibuk sendiri di wilayah yang memajang berbagai macam vas antik.
Kepala Sekolah Seo mendekati mereka bertiga, menyuruh Jisoo menanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai koleksi Kepala Sekolah Seo. Sialnya ketiga orang itu malah berbincang-bincang dengan seru, mengakibatkan Jisoo tidak bisa ke mana-mana dan harus menerjemahkan.
Matanya tak lepas dari cermin yang kini dikelilingi beberapa orang pengagumnya. Dua orang di antaranya, menarik perhatian Jisoo. Mereka berdua masih sangat muda untuk ukuran kolektor barang antik, kira-kira seusianya atau lebih tua setahun dua tahun darinya. Kedua pemuda itu sangat serius mengomentari cermin itu bahkan salah satunya diam-diam memotret cermin itu dengan kamera ponsel.
Jisoo tidak yakin mereka itu kolektor, terutama karena kedua pemuda itu tidak peduli dengan koleksi lain kecuali cermin tersebut. Rasanya Jisoo sudah tak tahan untuk menguping pembicaraan mereka.
“Oh, Mr. Wyatt and Mr. Harper, what about that antique mirror? It looks really elegant.” Jisoo akhirnya memberanikan diri untuk mengajak kedua tamu Kepala Sekolah Seo itu menuju ke arah cermin. Kepala Sekolah Seo melemparkan pandangan bingung padanya. Jisoo membalasnya dengan senyum.
“You have a great sense of art, Young man.” Mr. Wyatt mengomentari selera Jisoo tentang cermin itu, “Indeed, that mirror is really beautiful.”
“Let’s check it out.” sahut Mr. Harper, sementara itu Kepala Sekolah Seo berpamitan untuk menyapa tamu-tamu lainnya.
Mr. Wyatt dan Mr. Harper menyapa kedua pemuda itu, lalu berkomentar pada Jisoo bahwa jarang sekali mereka melihat pemuda yang mengagumi barang antik. Jisoo tersenyum kecut—ia sama sekali tidak merasa kedua pemuda itu adalah pengagum barang antik.
Salah satu pemuda itu mengulurkan tangan mengajak Mr. Wyatt dan Mr. Harper berkenalan. Jisoo terperangah.
“Thank you, Sir. I admire the beauty within this antique mirror. Don’t you think so? And by the way, I’m Jeon Wonwoo. My late-uncle owns an antique store. Perhaps you’d like to see our collections someday.” Lelaki itu menyerahkan kartu namanya pada Mr. Wyatt dan Mr. Harper, kemudian ia membungkukkan tubuhnya.
“Dan cermin ini?” tanya Jisoo penasaran, “Apa dulu pamanmu yang menjualnya pada Kepala Sekolah Seo?”
“Ya,” jawab Wonwoo sembari tersenyum palsu. Jisoo mengernyit, “Mungkin kau juga ingin melihat-lihat koleksi barang antik di toko kami.” Ia juga menyerahkan kartu namanya pada Jisoo.
Jisoo teringat pembicaraan Seungcheol dan Seungkwan tentang pemilik toko barang antik yang mengusir mereka waktu itu. Apa mungkin pemuda ini?
Setelah menemani Mr Wyatt dan Mr Harper berkeliling, dua tamu asing itu membiarkan Jisoo menikmati pesta tanpa harus mengikuti mereka sebagai penerjemah. Jisoo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berdiri di dekat dua pemuda itu.
“Apa benar itu cermin yang sama?” tanya Wonwoo pada pemuda satunya yang sibuk menulis pesan di ponsel.
Jisoo terkejut karena nama Jeonghan disebut. Jadi dua orang ini adalah teman Yoon Jeonghan—yang muncul di pantulan Seungcheol?
“Ya, benar itu cermin yang sama.” Pemuda satunya menyahut pertanyaan Wonwoo. Dari arah belakang, Jisoo mengintip pesan yang dituliskan pemuda itu pada Jeonghan. Sekilas ia membaca nama Seungcheol disebut-sebut lantas pemuda itu mengepalkan tangan seakan menahan emosi, lalu memasukkan ponselnya ke saku celana.
Apa Seungcheol sedang bersama Jeonghan?
“Jeonghan-ssi sudah menjawab pesanmu, Mingyu-ssi?”
“Ya. Cermin itu memang cermin yang sama dengan cermin yang ada di gudang kampusku.”
Jisoo mengangguk-angguk paham. Ia baru mengetahui bahwa cermin itu ada sepasang. Sebenarnya Jisoo ingin memperkenalkan diri sebagai teman Seungcheol, namun mengingat wajah pemuda bernama Mingyu itu berubah marah saat membaca nama Seungcheol disebut, Jisoo mengurungkan niatnya.
Ia membaca kartu nama yang diberikan Wonwoo. Mungkin Seungcheol harus bicara pada Wonwoo.
***
Seungcheol menatap lelaki yang berjalan di sampingnya itu—Yoon Jeonghan semakin lama dipandang semakin menarik. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Jeonghan. Setelah semalam tidur di ranjang yang sama, Seungcheol tidak yakin perasaan apa yang menyelimuti hatinya. Ia kerap kali merasakan mulas bila Jeonghan tersenyum—seperti rasa mulas bila ia disuruh presentasi di depan kelas. Menghabiskan waktu di hari Minggu bersama Jeonghan ternyata menyenangkan, meski mereka hanya bermain game saja.
“Seungcheol-ssi, lihat ini.” Jeonghan membuyarkan lamunan Seungcheol dengan menunjukkan sebuah foto. Foto cermin itu, “Mingyu dan temannya sekarang berada di rumah pemilik cermin itu, Seo Dalsoo. Kebetulan teman Mingyu mengenal pemiliknya. Ini cermin yang kaulihat, kan?”
“Kepala Sekolah Seo?” Seungcheol membelalak, “Jadi teman-temanmu ada di rumah Kepala Sekolah Seo?”
“Ya. Cermin itu disimpan di ruangan khusus.”
“Hmm, apa aku harus menerobos masuk ke rumah beliau ya?”
“Apa kau sudah gila? Jangan berbuat nekat, Seungcheol-ssi.”
“Tapi kalau kita tidak bergegas bertindak, permasalahannya tidak akan selesai.”
“Kita pikirkan cara lain yang tidak perlu membuatmu melakukan hal ilegal. Kau masih SMA, Seungcheol-ssi. Jalanmu masih panjang. Apa kau mau reputasimu jadi jelek karena kau menerobos masuk ke rumah orang?”
Ia tidak ingin namanya ada di dalam data kepolisian. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin Jeonghan iba melihat wajah sedih Seungcheol karena ia merasakan kepalanya diusap oleh Jeonghan, seperti mengusap kucing peliharaan. Jantung Seungcheol serasa mau melompat keluar.
“Berhenti memasang wajah sedih seperti itu. Aku ingin melihat senyum Choi Seungcheol.” ujar Jeonghan. Seungcheol meringis, memamerkan deretan giginya yang rapi, “Aku suka sekali melihat senyuman Seungcheol-ssi. Jadi jangan pernah murung lagi, oke?”
Dalam hati Seungcheol berteriak. Selama ini ia menutupi semua cermin dengan selimut agar ia tidak perlu berdebar ketika melihat senyum Jeonghan, tapi sekarang berhadapan langsung dengannya, membuat lutut Seungcheol lemas. Di pikirannya berkelebat kejadian semalam saat tubuh mereka bersentuhan dan Seungcheol mati-matian menahan diri untuk tidak memeluk lelaki di sampingnya itu.
Seungcheol ingat semalam ia pura-pura mendengkur agar Jeonghan mengira ia sudah tidur. Ia bersumpah merasakan jemari Jeonghan menyentuh tiap jengkal wajahnya—menyentuh bibirnya—kenapa Jeonghan melakukan semua itu?
“Seungcheol-ssi, boleh aku bertanya?”
Balon-balon imajinasi Seungcheol pecah sewaktu mendengar suara Jeonghan. Ia menoleh, “Apa yang ingin kau tanyakan, hyung?”
“Seandainya... selamanya kita tidak bisa mengembalikan pantulan itu bagaimana?”
Ia tidak langsung menjawab. Selama ini ia adalah orang yang bersikap positif dalam menghadapi apapun, termasuk kejadian seperti ini. Sama sekali tak pernah terbersit di pikirannya deretan skenario cadangan apabila ia tidak bisa mengembalikan pantulannya.
Kalau boleh jujur, ia tidak keberatan melihat Jeonghan tiap kali bercermin. Yang keberatan adalah perasaannya. Terbiasa memandang wajah Jeonghan yang tanpa cela itu bisa berakibat fatal pada masa depan percintaan Seungcheol. Ia tidak membayangkan bila nantinya mempunyai kekasih, tapi saat bercermin ia memandangi Jeonghan. Bagaimana ia bisa bertahan?
“Kau.... keberatan ya?” Jeonghan menundukkan kepala. Suaranya lirih.
“Ti-tidak, hyung. Tapi aku memikirkan bagaimana kalau kekasihmu marah karena tiap hari kau memandangi pantulanku di cermin.”
“Aku tidak akan menerima orang seperti itu sebagai kekasih.”
Tanpa dipikir terlebih dulu Seungcheol menyeletuk, “Wah pasti lebih baik bila kau yang jadi kekasihku karena—” Menyadari kesalahan ucapannya, ia buru-buru menutup mulutnya. Apa-apaan itu? Berharap menjadi kekasih Jeonghan karena mereka memahami apa yang terjadi.
Seungcheol seharusnya meminta maaf, bukannya terus berjalan dalam keheningan, meninggalkan seribu pertanyaan di dalam diri Jeonghan.
“Kenapa tidak?”
Ia menoleh ke arah Jeonghan secepat kilat. Apa ia tidak salah dengar? Seakan waktu berhenti ketika Jeonghan seakan menantangnya dengan pertanyaan itu. Seungcheol menelan ludah.
“Seungcheol-ssi, aku hanya bercanda!” Jeonghan tiba-tiba menyikut lengannya kemudian ia sudah berjalan jauh meninggalkan Seungcheol yang masih terpekur di tempatnya. Jeonghan membalikkan tubuh ke arah Seungcheol. Senyum menghiasi wajah manisnya, “Kau tidak jadi mengantarku pulang, Choi Seungcheol?”
Candaan itu nyaris menghentikan detak jantung Seungcheol.
BERSAMBUNG
Meanie kencan pergi pesta bareng lalalala~~ Sial ah kurang banyak momen2nya.
Ini kami lagi bikin chapter 06 dan chapter 03 TEARS sebelum lebaran jadi biar libur lebaran kalian smua bisa makin asik kalo ada bacaan. Makanya kami lemburan dulu.
And what the hell... kambek-nya Cebongs unyu2 banged gak sih mereka? XD
Jadi pengen bikin adegan makan es krim.
Eniweeee... as usual, your vote, comment, subscribe, bahkan cuman mention manggil2 nama kita pun kita jabanin.
Thanks for reading~
Comments